PADA Mei 1984, di tengah udara musim semi London yang sejuk serta dibawah bayang bayang kabut gelap, saya menerima sebuah buku kecil namun penuh daya ledak intelektual dari Pak Damanik—Atase Pertahanan Republik Indonesia di KBRI London waktu itu.
Judul bukunya: "Two Minutes Over Baghdad" karya Amos Perlmutter. Sejak pertama membuka halaman-halamannya, saya langsung tenggelam dalam narasi militer yang lugas, tentang bagaimana Israel melaksanakan operasi udara dengan berani dan juga cepat serta sangat presisi terhadap reaktor nuklir Irak di Osirak, Baghdad.
Pada 7 Juni 1981, dunia dikejutkan oleh operasi militer yang hanya berlangsung dua menit namun mengguncang geopolitik global. Delapan jet tempur F-16 Israel, dikawal oleh pesawat F-15, melesat dari Negev, melintasi langit Yordania dan Arab Saudi, lalu menghantam tepat ke jantung program nuklir Irak: reaktor Osirak di Baghdad. Operasi ini dikenal dengan nama Operation Opera—dan dalam kisah yang ditulis Perlmutter tersebut, kita diajak mengikuti tentang bagaimana dalam dua menit di atas langit Baghdad, sejarah Timur Tengah diubah untuk selamanya.
Israel meyakini bahwa reaktor Osirak yang dibangun Irak dengan bantuan Prancis, bukanlah untuk kepentingan damai, melainkan awal dari program senjata nuklir Saddam Hussein. Perdana Menteri Menachem Begin tak mau mengambil risiko. Ia sadar betul, dalam dunia di mana satu rudal bisa menghancurkan seluruh kota, menunggu hingga ancaman menjadi nyata adalah sikap yang terlalu mahal. Maka, keputusan diambil: Israel akan bertindak sebelum bom atom Irak sempat dibuat.
Operasi ini bukan sekadar keberhasilan militer—tetapi juga merupakan sebuah demonstrasi profesionalitas dalam bingkai superioritas teknologi, intelijen, dan penguasaan wilayah udara. Para pilot terlatih secara presisi. Mereka tahu target. Mereka tahu waktu mereka hanya dua menit. Dan mereka tahu tidak boleh meleset. Salah satu pilot dalam misi itu adalah Ilan Ramon, yang kelak menjadi astronot pertama Israel dan gugur dalam tragedi Columbia. Ia mewakili generasi profesional militer sejati: diam-diam, presisi, dan loyal tanpa kompromi. Militer profesional, bukan militer politisi apalagi militer pengusaha.
Namun reaksi dunia internasional keras. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 487 yang mengecam keras tindakan Israel, menyebutnya pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan negara di udara. Tapi di balik kecaman itu, lahirlah preseden penting: serangan pre-emptive untuk mempertahankan eksistensi negara sah jika ada ancaman luar biasa. Apakah legal? Debatnya panjang. Tapi bagi Israel, bertahan hidup tidak selalu menunggu lampu hijau diplomasi.
Dalam konteks strategi militer, Operation Opera menjadi studi klasik tentang doktrin pencegahan dini (pre-emptive doctrine), yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak negara lain, termasuk Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya pasca 9/11. Peristiwa ini juga menandai era baru di mana operasi militer tidak lagi dibatasi oleh garis-garis batas geografis, tetapi oleh persepsi ancaman yang bisa datang dari ratusan bahkan ribuan kilometer jauhnya. Dunia masuk ke babak baru: siapa yang memiliki superioritas udara, maka dialah yang menentukan permainan.
Refleksi yang saya ambil dari membaca buku tersebut bukan semata-mata tentang keberanian Israel, melainkan tentang bagaimana sebuah negara mewajibkan dirinya untuk menjaga wilayah udaranya sendiri. Israel tidak menunggu serangan datang. Ia mengantisipasi, mengambil keputusan sulit, dan menerima segala konsekuensinya—diplomatik, politik, maupun moral. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang sangat berani, meski tentu tak lepas dari kontroversi.
Dari sudut pandang militer profesional, Operation Opera menunjukkan bahwa kunci keberhasilan bukan hanya pada kekuatan senjata, tapi pada penguasaan penuh terhadap ruang udara. Pesawat-pesawat itu bisa sampai ke Baghdad dan kembali tanpa satu pun ditembak jatuh, karena sistem pertahanan udara Irak waktu itu masih lemah dan terfragmentasi. Ini memberi pesan tegas: siapa menguasai udara, ia menguasai inisiatif dan ia menjadi pemenang.
Ada satu pesan penting dari peristiwa ini yang patut menjadi bahan renungan kita di Indonesia. Wilayah udara bukan ruang kosong. Ia bukan sekadar langit biru tempat pesawat sipil lalu lalang. Udara adalah dimensi strategis sebuah negara. Jika tidak dijaga, ia akan dipakai orang lain. Dan kalau sudah dipakai, Anda hanya bisa melihat dari radar—bukan mengusir.
Sayangnya, Indonesia hingga hari ini masih menghadapi realitas getir di mana sebagian wilayah udara nasional, terutama di kawasan strategis seperti Selat Malaka, justru dikukuhkan untuk berada di bawah pengelolaan negara lain. Ini bukan sekadar isu teknis penerbangan sipil. Ini adalah soal kedaulatan, keamanan nasional, dan martabat bangsa. Pendelegasian pengelolaan wilayah udara kita kepada Singapura selama puluhan tahun, bahkan diperpanjang kembali pada tahun 2022, telah menjadi titik lemah yang nyata dalam sistem pertahanan nasional.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran wilayah udara Indonesia—baik oleh pesawat sipil maupun militer asing—terjadi berulang kali. Bahkan menurut laporan pusat kendali pertahanan udara nasional, pesawat asing seringkali berhasil dideteksi memasuki wilayah kita tanpa izin dan bahkan sempat di-intercept oleh jet tempur TNI AU dalam posisi yang sudah jauh berada di dalam teritori nasional. Sayangnya, banyak pula yang luput karena keterbatasan bergerak dari AU kita selain radar dan sistem komando pertahanan udara yang belum sepenuhnya berdaulat dan terintegrasi.
Kita perlu belajar dari Israel bukan untuk meniru gaya militer ofensifnya, tetapi untuk membangun kesadaran strategis: wilayah udara itu rentan dan harus dijaga. Tidak boleh ada satu inci pun ruang udara nasional yang dibiarkan dalam kendali pihak luar, baik atas nama keselamatan penerbangan sipil maupun kerja sama regional. Dalam geopolitik modern, udara adalah wilayah paling rawan namun sekaligus paling menentukan. Jika kita tidak kuasai, jangan heran kalau kedaulatan kita bisa dicabut secara bertahap, tanpa suara, dari ketinggian 0 hingga 37.000 kaki.
Kita perlu belajar dari sejarah. Bukan untuk meniru serangan dua menit ke Baghdad, tetapi untuk memahami bahwa pertahanan udara bukanlah pilihan—ia adalah keharusan. Karena dalam geopolitik modern, ketika rudal bisa datang dalam hitungan menit, yang membedakan negara yang bertahan dan yang tumbang hanyalah satu hal: siapa yang menguasai Udara.
Catatan Penutup
Dari Pearl Harbor hingga Osirak, dan bahkan tragedi 9/11, semua menunjukkan satu hal: serangan paling berbahaya datang dari udara. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kedaulatan udara adalah urat nadi pertahanan bangsa. Dua menit di atas Baghdad hanyalah contoh, bahwa wilayah udara tidak pernah boleh dibiarkan kosong, apalagi di delegasikan untuk 25 tahun dan akan diperpanjang. Sungguh Naif. 
Penulis adalah pendiri Pusat Studi Air Power Indonesia


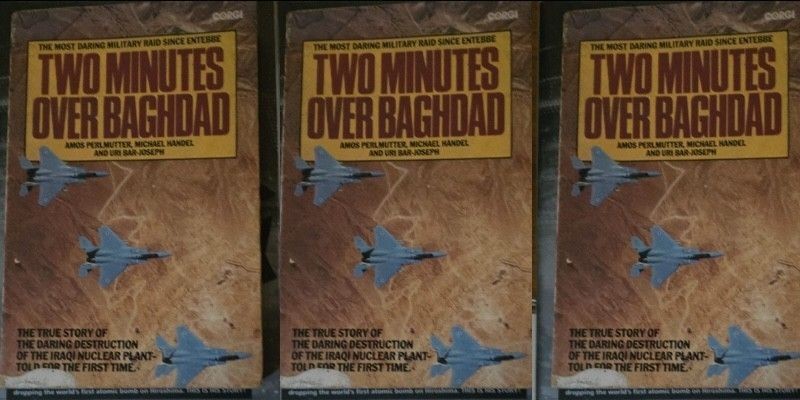

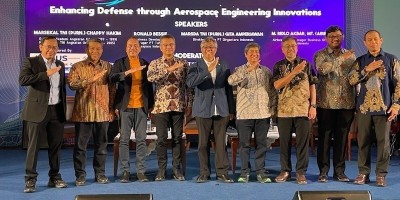








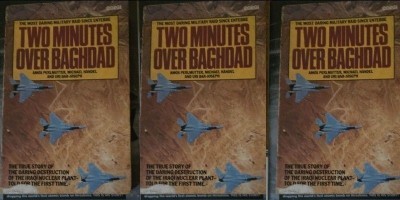


KOMENTAR ANDA